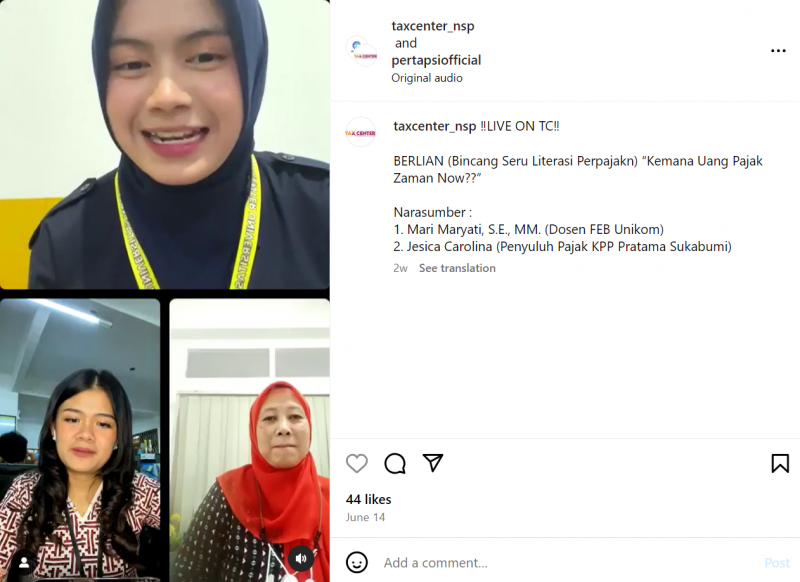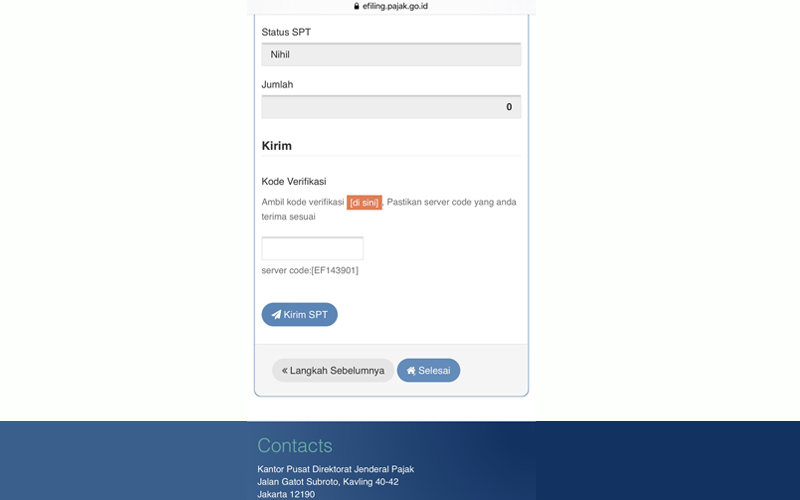Target penerimaan pajak ditentukan melalui perpaduan proses politik yang dilandasi beragam variabel, antara lain asumsi pertumbuhan ekonomi dan potensi pajak.
Di akhir atau awal tahun, sepertinya kita selalu memperdebatkan masalah tidak atau realistisnya target penerimaan pajak yang ditetapkan pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Sebelum ikut dalam perdebatan, penting bagi kita memahami penetapan target penerimaan pajak.
Managing Partner DDTC Darussalam mengutip DDTC Working Paper No 2119 berjudul “Metode dan Teknik Proyeksi Penerimaan Pajak: Panduan dan Aplikasi”, yang menjelaskan bahwa dalam perspektif politik anggaran, penentuan besaran target penerimaan pajak akan selalu diselaraskan dengan upaya mendanai belanja pemerintah tanpa memberikan suatu risiko fiskal yang besar. Perspektif itu merupakan kerangka sederhana yang melihat penentuan target penerimaan berdasarkan target belanja dan skenario pembiayaan anggaran.
“Walau sederhana dan merupakan perspektif dasar politik anggaran, cara tersebut tentu berisiko untuk meleset. Pasalnya, penentuan target tidak diperhitungkan secara matang dengan melihat kemampuan, tren, serta asumsi-asumsi di masa mendatang. Oleh karena itu, banyak pemerintah kemudian menggunakan pendekatan yang lebih teknis dan bisa dipertanggungjawabkan secara kuantitatif,” kata Darussalam kepada Majalah Pajak, pada (25/11).
“Sebagai contoh, melihat pola tax buoyancy atau elastisitas antara pertumbuhan ekonomi dengan pertumbuhan penerimaan pajak. Cara ini relatif sederhana karena hanya menggunakan indikator pertumbuhan ekonomi dan elastisitas secara historis serta asumsi pertumbuhan ekonomi di tahun fiskal ke depan. Namun, metode perhitungan ini relatif sulit dilakukan di situasi turbulensi ekonomi seperti saat pandemi Covid-19.”
Selanjutnya, perhitungan kuantitatif lainnya bisa menggunakan analisis ekonometri berupa data time series. Artinya, dengan melihat pola pengaruh atas berbagai faktor terhadap penerimaan pajak di suatu negara, maka akan diketahui besaran proyeksi penerimaan di masa mendatang. Variabel yang dipergunakan bisa bermacam-macam, semisal pertumbuhan ekonomi, pendapatan per kapita, inflasi, harga komoditas, perkembangan sektor tertentu, dan sebagainya. Berbagai pendekatan ini bisa disebut sebagai pendekatan berbasis data makroekonomi yang bersifat top-down.
Dalam berbagai teknik proyeksi penerimaan pajak, banyak akademisi menggunakan pertumbuhan ekonomi sebagai faktor penentu yang utama. Karena pertumbuhan ekonomi yang merujuk pada pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) merefleksikan pertumbuhan seluruh aktivitas ekonomi masyarakat serta adagium pajak sebagai ekor ekonomi. Sayangnya, keterkaitan antara pertumbuhan ekonomi dengan penerimaan pajak di Indonesia tidak terlalu tampak.
“Pembuktian dapat kita lihat dari data kinerja penerimaan pajak selama 10 tahun terakhir. Selama 1 dekade terakhir, target penerimaan pajak tidak pernah tercapai. Pada tahun fiskal 2015 dan 2016, realisasinya justru berada di bawah 85 persen dari target. Padahal, kita ketahui bahwa penyusunan target turut menyertakan variabel pertumbuhan ekonomi yang relatif stabil di atas 5 persen, kecuali pada 2020,” kata Darussalam.
Selain itu, perlu dipahami bahwa penganggaran merupakan proses yang cukup panjang. Pokok kebijakan fiskal beserta target penerimaan pajak tahun mendatang biasanya telah disusun sejak triwulan pertama tahun berjalan. Penyusunan itu umumnya juga menggunakan metode kuantitatif berdasarkan data historis sehingga dapat dipertanggungjawabkan (reliable).
Menariknya, bisa jadi terdapat dinamika sektor ekonomi, sosial, dan politik selama tahun berjalan yang membuat proyeksi tersebut sedikit menjauh dari kata presisi. Sebagai ilustrasi, proyeksi penerimaan di tahun mendatang telah disusun secara baik pada semester I tahun berjalan, tapi ternyata realisasi penerimaan pajak di tahun berjalan mengalami shortfall. Akibatnya, target tahun mendatang kian menantang dan ‘jauh’ dari angka yang realistis.
“Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah kini mulai menggunakan proyeksi outlook. Skema ini pada dasarnya berupaya untuk mendekatkan pada kondisi riil tahun berjalan,” kata Darussalam.
Selain itu, perhitungan target penerimaan pajak bisa saja disusun dari gabungan berbagai perhitungan di skala mikro. Caranya, nilai potensi penerimaan diukur berbasis perkembangan basis pajak dan dinamika di sektor atau jenis pajak tertentu.
“Dalam pendekatan mikro ini, cara perhitungan dan indikator yang dipergunakan bisa sangat bervariasi. Contoh, estimasi penerimaan PPnBM kendaraan bermotor dihitung dari jumlah penjualan dan impor setiap jenis kendaraan bermotor. Pendekatan mikro bersifat bottom-up dan umumnya lebih sering digunakan untuk mengukur dampak suatu kebijakan,” kata Darussalam.
Ia menilai, satu hal yang pasti penentuan target penerimaan pajak yang ideal adalah disusun secara kuantitatif melalui pendekatan teknis. Dengan demikian, risiko terjadinya shortfall atau defisit bisa lebih mungkin dikendalikan. Akan tetapi, hal yang perlu kita perhatikan adalah bahwa penentuan target penerimaan pajak juga suatu proses politik anggaran.
“Target pajak ditentukan dalam proses politik anggaran yang seringkali memadukan antara pendekatan yang bersifat teknis kuantitatif dengan kebutuhan belanja. Dalam prosesnya, aspek politik, yaitu faktor bargaining antara pemerintah dan DPR serta sasaran yang hendak dicapai mewarnai diskusi yang berpotensi menjauh dari target pajak yang realistis,” kata Darussalam.
UU HPP dan “tax ratio”
Ia menuturkan, bahwa kehadiran UU HPP sejatinya akan memutus persoalan fundamental sektor perpajakan tanah air. Terutama dalam turut menopang ketersediaan dana pembangunan yang kokoh dan berkelanjutan.
“UU HPP yang akan dilaksanakan mulai tahun depan adalah sesuatu yang tepat secara momentum. Karena jika kita baru mulai membahas reformasi pajak ketika pandemi berlalu, justru ada missed opportunity. Kehadiran UU HPP juga sejalan dengan agenda konsolidasi fiskal yang mulai banyak dilakukan oleh negara lain,” kata Darussalam.
Potensi keberhasilan UU HPP dalam meningkatkan tax ratio juga tidak bisa dilepaskan dari, antara lain, Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP), UU Cipta Kerja klaster kemudahan berusaha bidang perpajakan, pemberlakuan strategi compliance risk management, dan sebagainya. Namun demikian, masih ada tantangan.
“Adanya perubahan melalui UU HPP diproyeksikan bisa menghasilkan potensi penambahan penerimaan perpajakan. Akan tetapi, keberhasilan tersebut akan dipengaruhi oleh perilaku kepatuhan Wajib Pajak, serta literasi dan pemahaman seluruh pemangku kepentingan di sektor perpajakan. Selain itu, terdapat risiko distorsi pertumbuhan ekonomi akibat ancaman pandemi yang belum usai. Oleh karena itu, masih ada tantangan,” kata Darussalam.
Terkait aspek kepatuhan, ia memberikan catatan khusus. Berdasarkan buku berjudul Making People Pay: The Economic Sociology of Taxation (Mathew, 2010) setidaknya terdapat 10 aspek yang menentukan seseorang tidak patuh membayar pajak, yaitu tidak mendapat manfaat apa pun, pajak yang dibayar diselewengkan, pajak yang dibayar tidak digunakan dengan efisien, prosedur pajak sangat rumit, kesulitan memahami hukum pajak, interaksi dengan otoritas pajak tidak menyenangkan, khawatir diperiksa dengan tidak seharusnya, biaya kepatuhan pajak terlalu mahal, orang-orang sekitar tidak membayar pajak, dan merasa tidak memengaruhi penerimaan bila tidak membayar pajak.
“Jika kesepuluh hal tersebut dapat kita selesaikan, saya optimis kita bisa meningkatkan tax ratio lebih cepat. Sebagai contoh, upaya mengurangi biaya kepatuhan bisa dilakukan dengan menggunakan teknologi informasi, mencegah dan menyelesaikan sengketa pajak secara efektif dan efisien, pengaturan konsultan pajak agar tidak terjadi monopoli profesi, dan sebagainya,” kata Darussalam.
*Tulisan ini pernah dimuat di https://majalahpajak.net/ dan rilis tanggal 20 Desember 2021